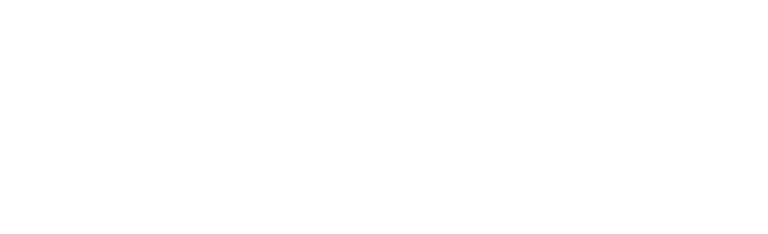Papua tak hanya kaya akan sumber daya alam. Budaya di tanah di timur Indonesia tersebut juga beragam. Di tengah lanskap alam yang mempesona, terhampar pula kekayaan adat istiadat yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dinamika hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang menyimpan kearifan lokal. Salah satunya tradisi otepuri yang dilakukan oleh suku Napiti yang mendiami wilayah Pulau Lakahia, Kaimana, Papua Barat.
Tabu Budaya dan Mediasi Sosial
Menurut Kepala Suku Napiti, Frans Amerbay, dalam budaya Napiti, terdapat berbagai tabu sosial yang mengatur interaksi antaranggota keluarga, seperti larangan bagi menantu dan mertua untuk berinteraksi langsung atau memanggil nama. Dalam konteks ini, kayu digunakan sebagai media komunikasi tidak langsung, sebuah bentuk mediasi adat yang menjaga tata krama dan keseimbangan sosial. Masyarakat menyebutnya otepuri.
Makna dan Asal Usul
Otepuri berasal dari Bahasa Napiti, yang terdiri dari dua kata: “Ote” yang berarti kayu dan “Puri” yang berarti pamali (hal tabu atau sakral). Praktik ini menggunakan kayu untuk menyampaikan keluhan atau protes, terutama oleh perempuan terhadap laki-laki.
Baca Juga: Tradisi Berburu dan Meramu Suku Irarutu di Teluk Bintuni
Pada masa lalu, perempuan yang secara sosial dianggap lemah diberi kesempatan untuk “memukul” laki-laki atau orang yang lebih tua —yang secara adat dianggap pamali– sebagai bentuk balas dendam simbolis atas perlakuan tidak adil. Melalui tindakan ini, perempuan menyuarakan harga diri, posisi, dan hak untuk dihargai, sekaligus membalik norma sehari-hari yang menuntut mereka menghormati laki-laki lebih tua.
Konteks Sosial dan Gender
Secara tradisional, laki-laki Napiti berperan sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan sering terpinggirkan dalam ranah sosial dan keluarga. Dalam hubungan rumah tangga, istri kerap mengalami perlakuan kurang adil baik dari suami maupun keluarga besar pihak laki-laki. Otepuri memberikan ruang simbolik bagi perempuan untuk menegaskan kesetaraan dan menuntut penghormatan. Tradisi tersebut bisanya dilakukan di setiap acara tahun baru masehi.
Evolusi Praktik Otepuri
Seiring waktu, makna Otepuri berkembang. Dari praktik fisik yang berakar pada rasa sakit dan pembalasan, kini Otepuri bertransformasi menjadi simbol cinta, pengakuan, dan kesetaraan gender. Otepuri kini bertransformasi menjadi wadah untuk menyatakan “kasih sayang”.
Baca Juga: Tradisi Wor dan Ungkapan Syukur atas Hasil Alam
Selain dilaksanakan pada acara adat, tradisi ini juga rutin diadakan setiap awal tahun, sekitar tanggal 3-5 Januari. Penyelenggaraan di awal tahun ini bertujuan untuk memeriahkan perayaan Natal dan Tahun Baru, serta yang terpenting, sebagai wadah “rekonsiliasi” antar keluarga setelah setahun hidup berdampingan yang mungkin menimbulkan masalah atau konflik. Otepuri juga menjadi media untuk berkomitmen kembali membangun hidup damai dan lebih harmonis antar keluarga dan masyarakat di tahun berjalan. Praktik modern dipahami sebagai perayaan budaya yang menekankan saling menghormati antara perempuan dan laki-laki, tanpa kekerasan.
Perubahan Media: Dari Kayu ke Sagu dan Lumpur
Dalam praktik kontemporer, Otepuri tidak lagi menggunakan kayu, melainkan bahan alami seperti sagu dan lumpur. Kaum Perempuan menggosok kaum laki laki dengan sagu ataupun lumpur.
Pergeseran ini mencerminkan nilai baru yang menekankan kelembutan, kehidupan, dan keterikatan dengan alam. Sagu dan lumpur memiliki makna penting sebagai sumber pangan dan simbol hubungan spiritual dengan tanah, menegaskan bahwa makanan tradisional bukan sekadar kebutuhan, tetapi bagian dari identitas dan kesinambungan budaya.
Editor: Nur Alfiyah