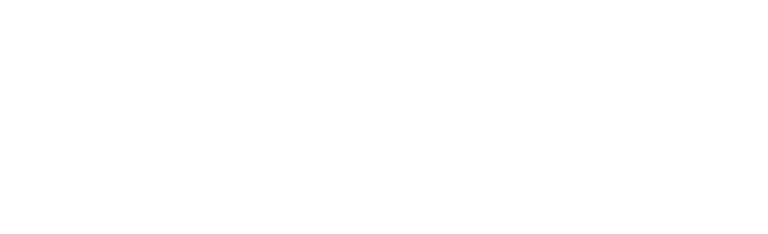“Miskin di atas kekayaan.” Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut seorang bapak suku di Kampung Kawaf, Kabupaten Teluk Bintuni. Suaranya lirih, namun tegas. Kata-kata sederhana yang seakan menampar siapa pun yang mendengarnya. Mereka hidup di tanah yang dipenuhi hutan primer yang lebat, hutan sagu, kebun pala, kepiting bakau, dan burung-burung endemik Papua. Namun kehidupan sehari-hari tetap sulit: air bersih langka, akses menuju pasar hampir mustahil, dan kebun mereka pernah hancur oleh perusahaan. Malam itu pada Agustus 2025, di rumah papan sederhana dengan cahaya lampu berasal dari generator yang berbunyi, saya mendengar langsung paradoks itu: kaya sumber daya, tapi miskin dalam kenyataan.
Siang hari sebelumnya, kami: tim dari EcoNusa dan Universitas Papua, menembus Sugueru, hutan sekunder tua yang masih menyimpan luka. Kami menyusuri hutan untuk melakukan survei keanekaragaman sumber daya alam dan potensi ekonomi Kampung Kawaf. Jalan bekas perusahaan kayu masih terlihat, licin, penuh akar, kadang harus meniti batu kapur tajam. Jarak yang harus kami tempuh tidak main-main: enam belas kilometer pulang balik. Napas memburu, kaki berat, dan tubuh basah oleh peluh yang bercampur bau tanah lembab. Pohon-pohon pionir seperti kalanggo (Duabanga moluccana) tumbuh rapat, menutupi bekas luka masa lalu, seakan hutan sedang berusaha menutup ingatannya sendiri.
Kami terus berjalan hingga ke hutan Swaroh. Menjelang senja, saat langit mulai berwarna jingga pucat di balik pohon-pohon besar yang menjadi kanopi, hutan memberi kejutan. Dari semak terdengar suara berat, “whoop… whoop…” Kami berhenti serentak. Seekor mambruk (Goura cristata) berjalan anggun di lantai hutan Swaroh. Tubuhnya besar, bulu biru keabu-abuan berkilat tersapu cahaya sore, mahkota di kepalanya menjuntai indah seperti kipas kerajaan. Hanya sebentar ia menampakkan diri, lalu hilang ditelan rimbun. Namun sejenak itu cukup: rasa letih seakan lenyap, terganti oleh syukur yang tak terucap. Hutan seolah berkata: “Aku masih ada.”

Hutan Swaroh sendiri seperti katedral hijau. Pohon-pohon raksasa berdiri tegak, batangnya hitam berlumut, akarnya mencengkeram tanah dengan gagah. Masyarakat mengenal kayu-kayu di dalamnya sebagai kayu besi dan kayu matoa, nama yang lahir dari keseharian mereka dan masa lalu bersama perusahaan, bukan dari buku. Bagi mereka, kayu besi adalah kekuatan, sedangkan matoa adalah manisnya buah yang dinikmati anak-anak. Saya belajar bahwa bagi orang kampung, pohon bukan sekadar spesies, melainkan bagian dari ingatan dan rasa.
Dari hutan, perjalanan berlanjut ke logpond lama, sebutan untuk area yang dulunya adalah kolam atau tempat penampungan kayu gelondongan, di pesisir. Bekas perusahaan kayu itu kini berubah jadi hutan mangrove. Akar-akar bakau menjuntai seperti jaring raksasa, menahan lumpur dan gelombang. Saat kami menapaki tanah hitam yang lengket, bau asin bercampur anyir menusuk hidung. Di antara akar, kepiting bakau berlarian masuk ke lubang. Bagi masyarakat, kepiting adalah emas hidup. Namun mereka punya aturan sederhana: ada waktunya diambil, ada waktunya dibiarkan. Pengetahuan yang tak tertulis itu menjaga mangrove tetap subur, bahkan lebih kokoh dari undang-undang.
Tak jauh dari sana, dusun sagu terbentang seperti halaman rumah raksasa. Batang-batang sagu berdiri rapat, daunnya berdesir tertiup angin. Sagu adalah nadi pangan: dari pati putih yang jadi papeda, sampai batang busuk yang menjadi makanan babi hutan. Masyarakat menebang pohon sagu, membiarkannya rebah, lalu memasang jerat untuk menangkap babi hutan. Pohon sagu yang busuk juga menjadi sarang bagi ulat pohon sagu, sumber protein lain bagi masyarakat kampung. Satu ekosistem sederhana, tapi sempurna: tumbuhan, satwa, dan manusia terhubung dalam lingkaran yang rapuh namun setia.
Baca Juga: Menjaga Hutan, Menjaga Kehidupan di Sorong Selatan
Dekat dengan hutan, juga ada kebun-kebun pala yang ditanam oleh masyarakat. Semua kekayaan itu seharusnya cukup untuk menghidupi mereka. Tapi kenyataan jauh dari indah. Untuk menjual pala, ongkos perahu sering lebih mahal dari harga jual. Untuk air bersih, mereka harus menampung hujan atau menggali kolam karena tanah karst menyembunyikan air di perut bumi. Dan luka lama masih terasa. Masyarakat masih ingat bagaimana kebun pala mereka diratakan saat perusahaan masuk. Kini kabar tentang jalan Trans Papua hanya menambah cemas. Jalan yang bagi orang luar berarti “kemajuan,” bagi mereka berarti kemungkinan kehilangan lagi: kehilangan hutan, kehilangan kebun, kehilangan hidup.
Malam itu kami kembali ke kampung untuk beristirahat. Suara jangkrik berpadu dengan gemericik hujan di atap seng. Di dalam rumah papan, kami duduk bersila, mendengar cerita satu demi satu. Seorang bapak menunduk lalu berkata, “Kami ini miskin di atas kekayaan.” Kalimat itu menggantung lama, lebih lama dari suara hujan.
Saya menutup catatan hari itu dengan perasaan campur aduk. Survei biodiversitas di Kawaf mengajarkan bahwa hutan bukan sekadar data spesies. Ia hidup dalam suara mambruk di senja, dalam kepiting yang bersembunyi di akar bakau, dalam sagu yang memberi makan dan berburu, dalam kayu besi yang berdiri kokoh, dan dalam cerita manusia yang bertahan di tengah keterbatasan. Biodiversitas di sini bukan hanya soal alam yang kaya. Ia adalah cerita tentang manusia yang berjuang, tentang paradoks “miskin di atas kekayaan,” dan tentang hutan yang masih bernapas meski penuh luka.
Editor: Nur Alfiyah