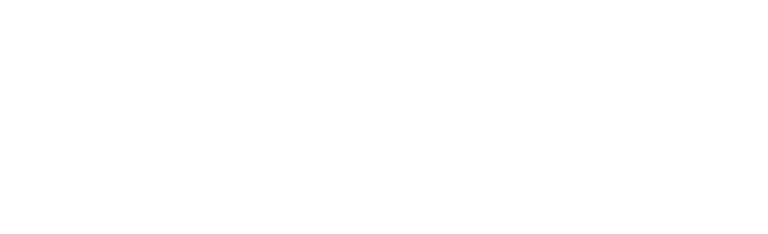Kampung Matara di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, merupakan satu dari sekian banyak kampung adat di Papua Selatan yang bergantung pada hasil alam. Kampung tersebut dihuni oleh 188 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 708 jiwa. Namun, rata-rata pendapatan warga masih di bawah Rp 400.000 per bulan.
Sebagian besar warga Matara bekerja sebagai petani atau nelayan. Para petani rata-rata mengelola lahan seluas 1-2 hektare per keluarga. Saat musim hujan tiba, mereka menanam padi. Jika hasil panen sedang melimpah, sebagian dijual untuk menambah penghasilan. Namun jika panen tidak maksimal, padi disimpan untuk konsumsi sendiri dan dijadikan benih untuk musim tanam berikutnya. Selain padi, para petani juga menanam palawija dan pisang. Namun menurut warga, fluktuasi harga menyebabkan perawatan terhadap tanaman ini, terutama pisang, tidak dilakukan secara rutin. Banyak kebun pisang yang dibiarkan begitu saja.
Baca Juga: Potensi Kelapa Nabire: Menjawab Tantangan Distribusi dan Harga lewat Kolaborasi
Untuk mengatasi hal itu, Mama Irene Mahuze mengatakan, ada inisiatif dari Pastor Paroki untuk menyelenggarakan festival Daun Anggai yang melibatkan empat kampung: Sirapuh, Urumb, Waninggap Nanggo, dan Matara. “Dalam festival tahunan tersebut, masyarakat mengumpulkan hasil tanaman seperti pisang dan umbi-umbian kemudian dilelang kepada pengunjung yang datang,” kata warga Kampung Matara tersebut.
Potensi Kelapa dan Udang
Di Matara, masyarakat juga menanam kelapa. Ada sekitar 6.000 pohon kelapa di sekitar kampung tersebut, belum termasuk kelapa yang ada di dusun masyarakat. Sebagian besar dari mereka menjual buah kelapa utuh. Dengan kenaikan harga kopra, masyarakat pun terimbas kenaikan harga kelapa. “Naiknya harga kopra juga memicu naiknya harga buah kelapa, di Kampung Matara pembeli membeli seharga Rp. 3000 per buah kelapa,” kata Kamilus Mahuze, mantan Sekretaris Kampung Matara.

Sekitar tahun 2000-2010, kata Kamilus, masyarakat sebenarnya juga mengolah kelapa menjadi kopra. Namun, karena harga kopra yang tidak stabil, masyarakat lebih memilih menjual kelapa utuh. Saat ini hanya satu warga yang membuat kopra. Buah kelapa yang sudah diolah menjadi kopra dibeli pengepul seharga Rp.15 ribu-17 ribu.
Dalam budaya masyarakat Matara, kelapa tidak hanya dianggap sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Berdasarkan kesepakatan adat antara ketua adat dan kepala marga, warga dilarang menjual kelapa muda. Hanya kelapa tua yang diperbolehkan dijual. Larangan ini berkaitan dengan fungsi kelapa dalam kehidupan sehari-hari. Sabut kelapa dimanfaatkan sebagai bahan bakar pengganti kayu, tempurungnya dijual, sementara daging kelapa menjadi bahan baku minyak atau pakan ternak.
Baca Juga: Kopra: Sumber Penghidupan dari Pulau Pai dan Kampung Yamnaisu
Untuk mendukung alternatif pendapatan, sejumlah warga membentuk kelompok usaha bernama Make Sasahi, yang dalam bahasa Marind berarti “mari bekerja.” Kelompok ini bergerak di bidang pengolahan hasil alam, seperti pembuatan minyak kelapa, virgin coconut oil (VCO), dan terasi udang. Pemerintah daerah melalui Dinas Perindustrian serta lembaga swadaya masyarakat telah memberikan dukungan berupa pelatihan dan peralatan produksi seperti mesin parut kelapa dan mesin cetak terasi. Namun, pelaksanaan kegiatan kelompok masih menemui kendala. Pada akhirnya hanya satu orang yang masih memproduksi, yakni Mama Elisabeth Gelambu.
Menurut mama Elisabeth, saat ini produksi VCO, minyak goreng, dan terasi kelapa tersebut dibantu oleh kedua anaknya. Mereka baru memproduksi jika ada permintaan dari para pelanggan. Sedangkan terasi diproduksi jika sedang musim udang. Terasi buat keluarga mama Elisabeth tersebut sangat diminati oleh masyarakat. Mereka bisa menghasilkan Rp.2-3 juta dari hasil penjualan. “Yang paling diminati itu terasi udang cetakan besar, sedangkan yang kecil bisa seminggu bisa habis terjual,” kata Mama Elisabeth.
Proyek Strategis Nasional
Proyek Strategis Nasional di Merauke juga berdampak pada masyarakat Matara. Warga mengetahui hal tersebut saat hendak menjaring ikan di sekitar hutan pada November 2024. Namun sesampainya di lokasi, mereka melihat hutan dan rawa sudah dibongkar. Karena itu, setelah bernegosiasi, dicapailah kesepakatan pelepasan. Tanah warga dibeli dengan harga Rp. 300 per meter dengan luas sekitar 250 hektare. Upacara pelepasan tersebut diselenggarakan pada 9 Agustus 2025 yang dihadiri oleh tujuh marga: Gebze, Mahuze, Kaize, Basik-Basik, Samkakai, Balagaize, Ndiken. Pelepasan ditandai dengan membunuh babi sebanyak 9 ekor. Ini dilakukan akibat penggusuran wilayah adat masyarakat tanpa proses sosialisasi maupun Padiatapa (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan).
Editor: Nur Alfiyah