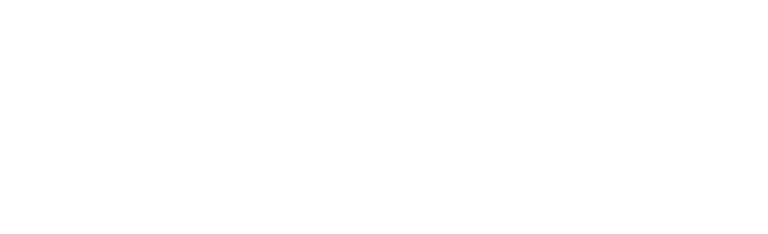Lokakarya Membangun Bioekonomi Restoratif Tanah Papua: Hak Masyarakat Adat, Alam Lestari, dan Kesejahteraan Bersama yang berlangsung di Hotel Vega, Sorong, menjadi forum strategis untuk merumuskan arah pembangunan Papua ke depan. Acara yang diinisiasi Yayasan EcoNusa bersama Kopernik ini mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan masyarakat adat untuk membicarakan gagasan bioekonomi restoratif sebagai jalan tengah antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian ekologi.
Dalam sambutannya, Maryo Saputra Sanuddin, Manager Regional Yayasan EcoNusa Papua, menegaskan bahwa bioekonomi restoratif adalah jalan yang dapat memastikan pembangunan Papua tidak mengorbankan lingkungan dan masyarakat adat. “Sejak 1960-an, konsep ini sudah dibicarakan. Namun kini kita menghadapi situasi yang semakin mendesak, di mana model ekstraktif terbukti hanya memberi manfaat pada segelintir pihak dan meninggalkan kerusakan ekologi,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa riset EcoNusa bersama Kopernik menunjukkan potensi luar biasa dari pendekatan ini. “Dalam dua dekade mendatang, bioekonomi restoratif berpotensi melampaui ekonomi ekstraktif, jika kita bersama-sama mendukungnya dengan kebijakan yang tepat.” Ia juga memaparkan capaian sembilan koperasi masyarakat adat yang dalam enam bulan terakhir berhasil menghasilkan pendapatan sebesar dua juta dolar Amerika. “Target kami hingga akhir tahun adalah empat juta dolar. Ini bukti bahwa ekonomi restoratif bukan sekadar konsep, melainkan praktik yang nyata dan memberikan hasil,” tegasnya.

Dukungan serupa datang dari pemerintah daerah. Sekretaris Daerah Papua Barat Daya, Drs. Yakob Karet, M.Si, menekankan pentingnya menjadikan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam pembangunan. “Masyarakat adat bukan objek. Mereka adalah subjek pembangunan, karena pengetahuan dan kearifan lokal mereka telah teruji mampu menjaga keseimbangan dengan alam,” katanya. Ia menekankan empat pilar yang harus menjadi acuan: perlindungan hutan dan ekosistem, penguatan hak-hak masyarakat adat, pengembangan ekonomi alternatif seperti hasil hutan bukan kayu dan ekowisata, serta penciptaan nilai tambah ekonomi tanpa merusak lingkungan. “Jika empat hal ini dijadikan pedoman, Papua dapat membangun tanpa harus kehilangan identitas, budaya, dan alamnya,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah pusat, melalui Bappenas, juga memberikan perspektif yang luas. Leonardo Adypurnama Alias Teguh Sambodo, perwakilan dari Bappenas RI, menguraikan posisi strategis Papua dalam konteks nasional dan global. Ia menjelaskan bahwa Papua memiliki lebih dari 20.000 spesies tumbuhan, 87 persen anggrek endemik, serta 3.000 jenis ikan yang menempatkannya sebagai pusat keanekaragaman hayati dunia. “Kekayaan ini bukan hanya milik Papua, tetapi juga aset nasional yang bisa menjadi penopang bioekonomi Indonesia,” ujarnya.
Leonardo menambahkan bahwa pemerintah telah mengintegrasikan isu keanekaragaman hayati dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045 dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041. Ia menegaskan bahwa bioekonomi harus dipandang sebagai strategi ganda: mendorong pertumbuhan ekonomi hingga delapan persen pada 2029 sekaligus memastikan keberlanjutan ekosistem. “Papua harus menjadi motor bioekonomi nasional. Tapi kita juga harus jujur: ancaman serius seperti alih fungsi lahan, pencemaran, dan marginalisasi masyarakat adat nyata adanya. Karena itu kuncinya adalah kolaborasi inklusif, di mana masyarakat adat menjadi aktor utama, bukan sekadar penerima manfaat,” ujarnya.



Setelah sambutan dan paparan kebijakan dari pemerintah pusat maupun daerah, lokakarya kemudian bergerak ke ranah analisis yang lebih mendalam. Diskusi panel pertama dibuka dengan serangkaian data dan kajian akademis yang memberi gambaran tentang situasi Papua hari ini sekaligus arah yang mungkin ditempuh di masa depan. Melalui sesi ini, peserta diajak melihat potret besar pembangunan Papua, bukan hanya dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari dampaknya terhadap hutan, masyarakat adat, dan keberlanjutan ekonomi daerah.
Sita Primadevi dari World Resources Institute (WRI) menjelaskan hasil pemodelan hingga 2050. Menurutnya, jika pembangunan tetap mengikuti pola Business as Usual, maka PDRB Papua memang meningkat, namun diikuti penurunan drastis tutupan hutan, lonjakan emisi karbon, serta menurunnya ketahanan pangan masyarakat adat. “Pertumbuhan makro tidak selalu berarti kesejahteraan masyarakat adat. Inilah kesenjangan pembangunan yang harus kita jawab,” tegasnya.
Dari perspektif ekonomi makro, Jaya Darmawan dari CELIOS menambahkan dimensi fiskal. Ia menilai tanpa instrumen pendanaan inovatif, bioekonomi restoratif sulit diwujudkan. “Kita butuh keberanian menerapkan pajak karbon, pajak keuntungan ekstraktif, bahkan pajak biodiversitas. Tanpa itu, restoratif tidak akan mampu bersaing dengan ekstraktif,” jelasnya. Menurutnya, justru ekonomi restoratif yang lebih menjanjikan karena mampu menciptakan 35 juta lapangan kerja dalam 15 tahun ke depan. Data ini memberi jawaban konkret terhadap kekhawatiran WRI tentang kesenjangan kesejahteraan.
Kopernik kemudian memperlihatkan wajah nyata dari potensi tersebut di lapangan. Chandra Dewanto memaparkan hasil pemetaan 38 organisasi akar rumput di Papua. “Nilai ekonomi restoratif saat ini sekitar Rp1,3 triliun. Tapi dengan mengalihkan 30 persen tenaga kerja pertanian ke praktik restoratif, nilainya bisa melonjak ke Rp130 triliun. Potensi tenaga kerja asli Papua yang terserap mencapai lebih dari setengah juta orang,” ungkapnya. Ia menekankan bahwa kunci keberhasilan ada pada penguatan kapasitas masyarakat, akses pendanaan, dan pengakuan hak ulayat. Dengan demikian, paparan Kopernik memberi gambaran bagaimana proyeksi dan instrumen fiskal bisa diterjemahkan ke praktik nyata di tingkat kampung.





Jika pada panel pertama peserta diajak menelaah data, proyeksi, dan instrumen kebijakan untuk mendukung ekonomi restoratif, maka panel kedua membawa diskusi ke ranah praktik nyata di lapangan. Sesi ini memperlihatkan bagaimana konsep besar bioekonomi restoratif diterjemahkan dalam bentuk inisiatif masyarakat adat, koperasi, dan usaha lokal yang sudah berjalan. Dari kisah-kisah tersebut, tampak bahwa Papua tidak hanya memiliki potensi, tetapi juga bukti nyata bahwa ekonomi berkelanjutan bisa tumbuh dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Angelius Mangatasi Nababan dari Mitra BUMMA menuturkan tentang BUMMA Namblong di Kabupaten Jayapura. “BUMMA adalah badan usaha milik masyarakat adat yang sepenuhnya dikelola oleh suku-suku. Dengan wilayah lebih dari 52 ribu hektar, kami berhasil menjaga hutan tetap utuh dengan tingkat deforestasi nol persen. Ekonomi adat tetap berputar, menghasilkan 5,5 miliar rupiah per tahun, dengan biaya pengelolaan yang relatif rendah,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa prinsip Menoken, Membumi, Membumma menjadi dasar gerakan ini: merajut solidaritas, memulihkan tanah, dan membangun kedaulatan ekonomi adat.
Etik Mei Wati dari KOBUMI menambahkan pengalaman serupa lewat jaringan koperasi di Papua dan Maluku. “Kami mengelola komoditas seperti pala, kopra, cengkeh, udang, dan tuna. Target kami pada 2025 ambisius, misalnya 400 ton pala dan 25 ton tuna. Tapi semua ini dikerjakan oleh masyarakat lokal dengan sistem berkelanjutan,” ujarnya. Ia menekankan bahwa keuntungan kembali kepada masyarakat melalui koperasi. Pernyataan ini membangun kesinambungan dengan pengalaman BUMMA: bahwa model restoratif dapat tumbuh melalui wadah kolektif yang dikelola komunitas.
Koperasi Ebier Suth Cokran memberi warna lain dengan inovasi agroforestri. Flandy Roberti Botto menjelaskan, “Kami beralih dari monokultur kakao ke dynamic agroforestry. Hasilnya bukan hanya panen beragam, tapi juga tanah tetap subur tanpa pupuk kimia.” Ia menambahkan bahwa seluruh pekerja mereka adalah orang asli Papua. “Kami sudah menembus pasar internasional, dengan harga premium karena produk organik. Ini bukti bahwa Papua bisa bersaing di pasar global,” ujarnya. Kisah ini menghubungkan potensi lokal dengan pasar internasional, melengkapi gambaran bahwa bioekonomi restoratif dapat berdiri sejajar dengan ekonomi modern.



Lokakarya ditutup dengan komitmen bersama menyusun rencana aksi jangka pendek, menengah, dan panjang. Dalam dua tahun pertama, fokus diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat dan harmonisasi kebijakan. Pada tiga hingga empat tahun berikutnya, perhatian tertuju pada pengembangan ekowisata dan hasil hutan bukan kayu. Pada tahun kelima, bioekonomi restoratif ditargetkan menjadi arus utama pembangunan Papua.
Keseluruhan pertemuan ini menguatkan satu pesan: Papua adalah jantung bioekonomi Nusantara. Dengan kekayaan hayati yang luar biasa dan masyarakat adat sebagai penjaga utama, Papua berpotensi menjadi contoh pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan ekologi, budaya, dan kesejahteraan. Seperti ditegaskan Nur Maliki Arifiandi dari Koalisi Ekonomi Membumi, “Bioekonomi restoratif adalah masa depan Indonesia. Dari inisiatif lokal, kita harus menjadikannya gerakan nasional yang berpihak pada alam dan manusia.”